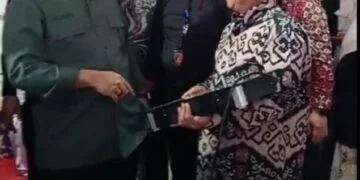IMBCNEWS Jakarta | Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Indonesia Prof. Dr. Jimly Asshidiqie kembali menegaskan, saya turun mau menjadi sebagai saksi ahli dalam kasus Juditial Revew atau uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstiusi, karena demokrasi Indonesia sudah kian gawat, diperkirakan akan terus turun jika tidak ada perbaikan konstitusi.
Lebih dari 30 penggugat terhadap Pasal 222 terkait dengan Electoral presidential threshold 20 persen dari perolihan kursi DPR, digagalkan oleh Putusan MK karena tidak punya legal standing atau pasal itu bersifat open legal policy atau haknya DPR untuk mengatur.
“Menurut saya tidak begitu, pembatasan itu karena adanya ketakutan untuk bersaing untuk menjadi presiden, oleh karena itu saya berpendapat untuk dibuka saja bebaskan partai untuk mencalonkan tanpa perlu pembatasan. Di Rusia yang terkenal sebagai negara tertutup saja, calon Presiden sampai 34 orang yang pada akhirnya rakyat Rusia masih memilih Vladimir Putin sebagai presiden,” kata Prof. Dr. Jimly, menjawab pertanyaan imbcnews dalam diskusi “Ngaji Konstitusi yang diselenggarakan oleh Jimly School Of Law and Government (JSLG) di Jakarta, Jumat.
Diskusi yang dipimpin Dr. Wahyu Nugroho dengan nara sumber Prof. Dr. Taufiqurahman Syahuri, Titi Angraini, SH MH dan Dr. Jamalludin Ghafar, dosen dari Univeritas Islam Indnesia (UII) Yogjakarta, Jimly menambahakan, selama ini, mungkin sudah 20 tahun saya tidak mau diundang sebagai ahli, karena putusan terakhir dalam gugatan konstitusi ada di hakim Mahkamah. “Saya tidak mau lagi, saya sebagai mantan Ketua MK dan lain sebagainya, biarlah hakim MK memutuskan,” katanya.
Menurut dia, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, soal penghapusan ambang batas dalam pencalonan presiden alias presidential threshold 20 persen, bakal banyak anak bangsa yang bakal mencalonkan diri sebagai calon presiden di Pilpres 2029.
Pasti akan lebih banyak capres, dan tentunya akan membuat demokrasi makin berkembang karena Indonesia negara besar dengan Bhineka Tunggal Eka. Oleh karenanya, ia meyakini penghapusan ambang batas presiden itu dapat membuat capres makin beragam etnisnya. Sehingga capres tak hanya didominasi suku tertentu saja.
“Itu menyalurkan suara boleh keturunan Aceh, Papua. Soalnya terpilih atau tidak belakangan. Kalau di tingkat kabupaten kota sudah ada biar inklusivisme demokratis makin berkembang.”
Meski demikian, lanjut Jimly, dirinya menilai harus ada mekanisme yang membatasi jumlah pasangan calon (paslon). Sebab, perlu modal tingkat elektabilitas yang tak sedikit. Sehingga Jimly menduga jumlah capres tak akan mencapai belasan orang.
“Misal ndak mungkin lebih banyak dari 9 (capres) karena biayanya mahal Pilpres dan bohir-bohirnya juga ngitung potensi menangnya. Nggak ada orang mau buang uang percuma,” ucap Jimly.
“Jadi masyarakat akan ngerem sendiri, ada mekanisme kontrol sendiri. Jadi dari jauh hari nggak usah takut kebanyakan. Wong belum dites, belum dicoba. Simpan dulu ketakutan banyak calon,” tambahnya.
Sedang, Prof. Tafiqurahman Syahuri, dosen Universitas Veteran Jakarta, menambahkan sejak lama saya sudah mengingatkan electoral presidential treshold yang terdapat dalam Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 sudah lama saya kritisi lewat jurnal hukum.
Menurut dia, meskipun Indonesia sebagai negara demokrasi, tidak berarti boleh menyepakati berbagai hal yang bertentangan dengan hak asasi manusai atau asas kepatutan masyarakat. “Calon prsiden Indonesia itu seyogianya sejak awal sudah di cek kesehatannya, atau integritasnya saat belum ditetapkan KPU. Kalau sudah ditetapkan, tidak mungkin pihak lain akan berani mencoret,” katanya.
Syarat Parpol Jangan Dipersulit
Sementara itu, Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia (UI) sekaligus anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menilai, agar syarat partai politik peserta pemilihan umum tidak dipersulit, paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) usai menghapus ambang batas presiden atau Presidential Threshold untuk Pilpres Tahun 2029.
“Jangan sampai atau tidak perlu ada perubahan syarat partai politik menjadi peserta pemilu. Karena sekarang persyaratan yang ada itu sudah salah satu yang paling berat, paling mahal, paling rumit, paling susah di dunia,” jelas Titi.
Ia menjelaskan, syarat parpol peserta pemilu yang telah diatur dalam Pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah begitu sulit dan mahal.
Adapun beberapa persyaratan di antaranya ialah memiliki kepengurusan di 75 persen di jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, dan memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota.
Selain itu, menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik.
“Jangan ada upaya dari pembentuk undang-undang untuk menciptakan barrier to entry baru (hambatan untuk berkompetisi) bagi partai-partai non-parlemen,” kata Titi.
Terlebih, lanjut Titi, partai politik parlemen telah diuntungkan dengan adanya putusan MK Nomor 55/PUU/XIX/2020 yang memutuskan bahwa parpol parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual agar terdaftar sebagai partai peserta pemilu.
Titi mendesak, agar pemerintah dan DPR tidak melakukan manuver untuk memperberat partai non parlemen agar terdaftar sebagai partai politik peserta pemilu.
“Jangan sampai ada motif dari parlement untuk menghambat kompetitor dengan memperberat syarat menjadi partai politik peserta pemilu. Jangan lagi ditambah syarat yang aneh-aneh ini untuk motif menghambat kompetitor baru,” terang Titi.
Diketahui, MK menghapus ketentuan ambang batas presiden dalam UU Pemilu, usai mengabulkan perkara Nomor 64/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
imbcnews/sumber diolah/