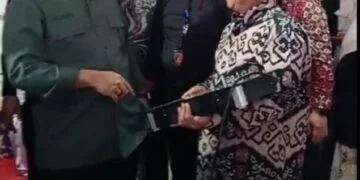Oleh Gita Ruslita, Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta
IMBCNEWS Jakarta | Di era digital ini, fenomena influencer telah menjadi wajah baru dari industri budaya populer. Mereka tidak hanya mempromosikan produk. Tetapi juga menawarkan gaya hidup, nilai-nilai, bahkan aspirasi yang nampak begitu ideal dalam masyarakat modern yang direfresentasikan di media digital, khususnya media sosial (medsos).
Namun, jika ditinjau lebih dalam, terdapat mekanisme yang jauh lebih kompleks di balik keberhasilan para influencer ini. Di balik kilau kesuksesan para influencer ini, ada dinamika yang mencerminkan logika kapitalisme dan homogenisasi budaya, sebagaimana dikritik oleh Theodor Adorno dan Max Horkheimer dalam konsep industri budaya dan penerangan negatif.
Adorno (1903-1969) dan Horkheimer (1895-1973), teoritikus generasi pertama Mazhab Frankfurt, Jerman, yang memiliki pandangan kritis terhadap kebudayaan dalam masyarakat kapitalis modern. Mereka mengungkapkan bagaimana budaya telah direduksi menjadi komoditas melalui fenomena industri budaya (culture industry). Dalam konteks Indonesia, fenomena ini semakin nyata.
Budaya lokal seringkali mengalami intervensi struktural dan marginalisasi demi mengakomodasi kebutuhan pasar yang berorientasi pada keuntungan materiil (Alkhajar, 2011, dalam Anugrah, 2014). Influencer, sebagai agen budaya populer, menjadi salah satu aktor dalam dinamika ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Budaya sebagai Komoditas: Kritik Adorno dan Horkheimer.
Keduanya melihat bagaimana budaya dalam masyarakat kapitalis berubah menjadi sekadar komoditas. Mereka memperkenalkan konsep industri budaya untuk menjelaskan bagaimana produksi budaya telah diambil alih oleh logika pasar.
Budaya, yang seharusnya menjadi ruang ekspresi dan refleksi manusia, kini direduksi menjadi alat untuk menggerakkan konsumsi yang mengutamakan keuntungan. Budaya yang dulunya dipandang sebagai medium untuk menyampaikan ide dan nilai kini diperlakukan sebagai barang yang bisa diproduksi, dijual, dan dikonsumsi. Dalam kerangka ini, budaya bukan lagi tentang kebebasan berpikir dan berkreasi, melainkan alat untuk merangsang konsumsi.
Fenomena ini dapat kita lihat dengan jelas dalam dunia influencer. Sebagai contoh, para influencer di medsos sering kali memproduksi konten yang tidak hanya bertujuan menghibur atau mendidik, tetapi lebih untuk mempengaruhi audiens agar membeli produk tertentu.
Narasi yang mereka ciptakan sering kali mengaitkan kebahagiaan, kesuksesan, atau kecantikan dengan konsumsi produk tertentu, seperti “pakai produk ini kulitmu akan putih dan mulus.” Meskipun konten ini terasa pribadi dan autentik, kenyataannya banyak dari konten tersebut yang dikendalikan oleh algoritma media sosial dan kebutuhan sponsor. Hal ini menyebabkan konten yang tampaknya unik dan personal sebenarnya tunduk pada tuntutan pasar dan mekanisme algoritma.
Selain itu, fenomena ini menghasilkan homogenisasi budaya, yaitu ketika keragaman nilai dan identitas budaya mulai tergerus, digantikan oleh standar yang lebih seragam dan didorong oleh kepentingan ekonomi. Kita dapat melihat bagaimana banyak konten yang dibuat hanya mengikuti tren tertentu, menggiring audiens ke dalam pola pikir dan perilaku konsumtif yang serupa, tanpa memberi ruang bagi keberagaman pandangan atau ekspresi budaya yang lebih dalam.
Dengan kata lain, media sosial menawarkan banyak kesempatan untuk berbagi ide dan kreativitas, algoritma yang mendasari platform ini justru cenderung memperkuat homogenisasi dan mengurangi keautentikan budaya. Dengan demikian, budaya yang seharusnya menjadi wadah untuk ekspresi individual kini sering kali terjebak dalam logika kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan daripada keberagaman dan kedalaman makna.
Ilusi Kebebasan dalam Konsumerisme
Adorno dan Horkheimer juga memperkenalkan konsep penerangan negatif untuk menggambarkan ilusi kebebasan yang ditawarkan oleh kapitalisme. Dalam dunia influencer, narasi seperti “jadilah versi terbaik dirimu” atau “pilihan ada di tanganmu” adalah bentuk ilusi tersebut. Padahal, pilihan yang tersedia sering kali telah diarahkan oleh tren pasar, algoritma, dan strategi pemasaran.
Sebagai contoh, masyarakat muda yang menjadi target utama influencer kerap merasa tertekan untuk mengikuti gaya hidup tertentu demi dianggap relevan. Alih-alih bebas, konsumerisme ini justru menciptakan ketergantungan dan memperkuat dominasi kapitalisme atas kehidupan sehari-hari.
Namun, penting untuk diingat bahwa Adorno dan Horkheimer tidak menganjurkan penolakan total terhadap budaya populer atau influencer. Sebaliknya, mereka mengajak kita untuk berpikir kritis. Influencer sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial. Mereka dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk mendukung nilai-nilai yang lebih inklusif, mempromosikan pelestarian budaya lokal, atau bahkan mengkritisi pola konsumerisme yang merugikan masyarakat.
Sebagai audiens, juga memiliki peran. Dengan memahami bagaimana konten budaya diproduksi, dapat menjadi konsumen yang lebih reflektif. Alih-alih mengikuti tren secara membabi buta, dapat mulai mempertimbangkan dampak dari pilihan konsumsi kita terhadap lingkungan, budaya, dan masyarakat.
Salah satu contoh nyata dari kritik Adorno dan Horkheimer tentang industri budaya dan penerangan negatif adalah bagaimana influencer menciptakan budaya baru yang mengaitkan produk tertentu dengan status sosial.
Sebut saja Iphone produk dari Apple. Lewat promosi tidak baik secara langsung atau tidak langsung dari para influencer di berbagai platform media sosial yang menggunakannya, Iphone kini telah menjelma menjadi simbol prestige dan kemapanan.
Di media sosial, influencer sering kali memamerkan Iphone sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Foto dengan Iphone terbaru di tangan, unboxing produk, atau video review penuh pujian menjadi cara mereka membangun citra bahwa Iphone bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol keberhasilan, gaya hidup modern, dan bahkan kecanggihan teknologi.
Efeknya, Anak muda, yang menjadi target utama influencer, merasa bahwa memiliki Iphone adalah “keharusan” agar dapat diterima dalam lingkungan sosial tertentu. Tidak peduli apakah mereka benar-benar membutuhkan teknologi tersebut, atau apakah perangkat lain sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini secara tidak langsung menciptakan tekanan sosial. Tekanan sosial ini menciptakan fenomena unik. Banyak anak muda kini rela memaksakan diri untuk memiliki Iphone, termasuk membeli Iphone second tanpa garansi resmi atau menggunakan jasa sewa harian.
Tren ini begitu marak sehingga toko-toko yang menjual Iphone second atau menawarkan jasa sewa kini bertebaran di berbagai kota. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Adorno sebagai homogenisasi budaya. Ketika masyarakat secara kolektif mengejar simbol-simbol yang sama karena dianggap keren atau “penting,” tanpa mempertimbangkan kebutuhan individu atau nilai fungsional produk tersebut. Iphone, dalam hal ini, telah kehilangan fungsi utamanya sebagai alat komunikasi dan berubah menjadi komoditas budaya yang dilandasi oleh logika kapitalisme.
Horkheimer menyebut ini sebagai penerangan negatif, di mana masyarakat dibuat percaya bahwa kebahagiaan atau pengakuan sosial dapat dicapai melalui konsumsi. Padahal, kebebasan yang ditawarkan oleh pilihan tersebut sebenarnya adalah kebebasan semu, karena masyarakat hanya diarahkan untuk mengonsumsi produk yang sudah ditentukan oleh pasar dan tren budaya populer.
Dampak dari fenomena ini tidak hanya pada aspek ekonomi, misalnya, anak muda yang memaksakan diri membeli Iphone meski kemampuan finansial mereka terbatas, termasuk dengan harus memaksakan diri meminjam uang melalui jasa paylater yang marah saat ini.
Lebih dari itu, ada dampak psikologis, seperti rasa tidak percaya diri jika tidak memiliki Iphone, atau kecemasan sosial karena dianggap “ketinggalan zaman.”
Dia mengingatkan kita bahwa budaya populer yang dikendalikan oleh industri sering kali tidak hanya membentuk preferensi konsumen, tetapi juga membentuk identitas dan hubungan sosial. Dalam kasus ini, kepemilikan Iphone menjadi simbol identitas dan status sosial, yang ironisnya justru membelenggu kebebasan individu.
Fenomena influencer, konsumerisme, dan budaya populer ini adalah refleksi nyata dari dinamika kapitalisme modern yang dikritik oleh Adorno dan Horkheimer. Budaya yang awalnya menjadi ruang ekspresi kini terjebak dalam logika pasar, mengutamakan keuntungan atas nilai-nilai kultural. Narasi yang dibangun oleh influencer, seperti kepemilikan Iphone sebagai simbol status sosial, menjadi contoh konkret homogenisasi budaya dan ilusi kebebasan yang diciptakan oleh industri budaya.
Hal ini tidak hanya memengaruhi preferensi konsumsi tetapi juga membentuk identitas dan relasi sosial, sering kali memperkuat ketergantungan terhadap kapitalisme.
Menghadapi realitas ini, kita perlu untuk menjadi konsumen yang kritis. Perlunya kesadaran diri bahwa tren budaya populer tidak selalu mencerminkan kebutuhan kita yang sebenarnya. Pentingnya edukasi diri dan hadirnya komunitas sosial yang lebih menghargai nilai dan kebutuhan individu di atas tekanan sosial. Sehingga harapannya, kita dapat menjaga keberagaman budaya lokal, mendorong pemanfaatan produk sesuai kebutuhan, dan melepaskan diri dari dominasi tren pasar yang homogen.
Memahami kritik Adorno dan Horkheimer ini dapat memberikan perspektif penting untuk menghadapi budaya populer di era digital. Kebebasan sejati bukanlah tentang mengikuti narasi yang dibentuk pasar, tetapi tentang membuat pilihan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai kita sebagai individu bebas. Sehingga melalui sikap kritis ini, kita tidak hanya menjadi konsumen pasif tetapi juga aktor perubahan yang berkontribusi pada masyarakat yang lebih terbuka, reflektif, dan berkeadilan.
** penulis juga sebagai Pegawai Kementerian Pendikian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.