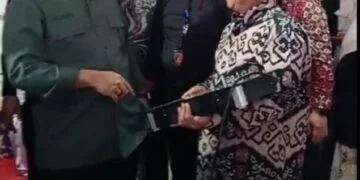Oleh Dr. Dedi Sahputra, pengamat komunikasi
IMBCNEWS Medan | Ketika perang panjang semakin melelahkan (1825-1830), Jenderal De Kock mengeluarkan senjata pamungkasnya. Dia mengerahkan para ilmuwan untuk mengkaji kebiasaan, adat budaya, sumber nilai, pola komunikasi, serta segala hal tentang lawan tandingnya, dialah Sang Penunggang Berkuda itu.
Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu itu adalah semuanya; selain seperangkat nilai yang dianut, juga data tentang siapa istrinya, anak-anaknya, sahabatnya, kebiasaan makannya, jenis makanannya, bahkan kebiasaan buang air pun tak luput.
Meminta bantuan “orang pintar” dilakukan De Kock setelah perang gelar tak berhasil, perang gerilya apalagi. Dana perang sudah habis berpeti-peti, bahkan anggota pasukan banyak yang sudah terbaring meregang nyawa, baik karena bertempur atau karena kelelahan, dan sakit di medan yang sulit. Dan kini yang diperlukannya hanya setumpuk kertas laporan hasil penelitian para kutu buku.
Ketika kesimpulan studi sudah di tangan, dia memiliki segala informasi tentang musuhnya itu. Maka ketika intelijen melaporkan keberadaan pasukan lawan sedang berada di hutan Remojatinegara, inilah keputusannya yang tak diduga, bahkan oleh kawanannya sendiri. Dia tidak memerintahkan pasukannya memborbardir dengan mesin-mesin perang. Tapi dia hanya memerintahkan seorang komunikator handal, ahli membujuk dan melakukan lobby untuk menemui Pangeran Diponegoro, Sang Penunggang Berkuda.
Sang pembujuk ini menawarkan perundingan kepada pangeran. Tapi putra sulung Sultan Hamengkubuwono III ini bukan tidak tahu akal bulus Belanda, tidak katanya. Namun bukan ahli namanya kalau lekas menyerah, Kolonel Cleerens, sang pembujuk ini terus menawarkan jalan perundingan dengan segala argumentasinya.
Di sinilah peran segudang data dan rekomendasi ilmuwan. Bahwa seorang ningrat terhormat seperti Pangeran Diponegoro tidak akan menolak jalan “kebaikan” yang berulang-ulang ditawarkan kepadanya.
Maka ketika ia akhirnya mengatakan “ya”—meski dengan segudang persyaratan, itu sama artinya sudah lebih separuh kemenangan Belanda. Dan di tepi sungai Bogowonto, Magelang, tempat yang dijanjikan untuk berunding, di situ pula sang pangeran ditangkap tanpa desingan peluru.
Apa yang dilakukan oleh De Kock jauh sudah berkembang dalam perang modern kini. Defenisi perang adalah menguasai pasca “fatwa” Malthus soal penguasaan sumber daya dunia.
Karena pertumbuhan sumber daya berdasarkan deret hitung (1,2,3…) sedangkan pertumbuhan manusia berdasarkan deret ukur (1,2,4,8…) maka rebut dan kuasailah sumber-sumber daya itu. Maka kemudian dimulailah ekspansi penjajahan dari daratan Eropa ke seluruh dunia.
Kemenangan perang adalah soal kalkulasi membaca lawan. Dan untuk sampai pada titik ini, harus ada satu kesadaran yang disebut: membaca diri. Hanya orang yang memiliki kemampuan membaca dirinya sendirilah yang akan sampai pada kesadaran untuk membaca lawan.
Maka barulah berlaku seperti kata Sun Tzu, bahwa pemenang itu adalah mereka yang paling mengetahui lawannya.
Inilah rahasia di balik ribuan jilid buku hasil penelitian tentang kecederungan sosial, budaya, komunikasi, politik dan lain sebagainya—yang dihasilkan para ilmuwan yang dikerahkan ke negara-negara dunia ketiga. Membacanya, Anda akan selalu menemukan “koneksi” dengan kebijakan luar negari negara-negara kapitalis dunia.
Maka ucapan Khalifah Umar bin Al Khattab 1.400 tahun lalu seolah menemukan metaforanya–ketika ia berkata: hisablah dirimu sebelum dihisab, dan timbanglah sebelum ia ditimbang… Hanya ketika engkau mengetahui kesalahan-kesalahanmu, engkau akan beranjak lebih baik.
Atau ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib menasihati bahwa, sebuah kejahatan yang dimenej akan mengalahkan kebaikan yang hanya dikelola apa adanya.
Nama Khawarij serta merta terkenal identik dengan akal yang terpinggirkan. Bahwa tindakan yang dilakukan hanya melandasi diri dari “rasa” yang melintas. Siapapun yang tidak sesuai dengan kita, libas saja, halal darahnya. Tapi sesungguhnya ia tak serta merta soal memingirkan akal, tapi ia juga soal egosentrisme.
Dan inilah yang paling mengejutkan, bahwa fenomena Khawarij tidak hanya bertahan hidup tapi juga berkembang melintasi zaman. Ia melekat di individu yang ambisius, di keserakahan yang menegara, tak terkecuali ambisi kapitalisme yang meniscayakan perang sebagai jalan yang rasional untuk mencapai tujuan.
Dan dirimu tidak akan pernah bisa berbuat apapun sampai engkau memutuskan untuk menjadi pribadi yang kuat. Ini kualitas pribadi yang mustahil dicapai tanpa melalui kesadaran membaca diri sendiri.
Penulis tingal di Medan, Sumatera Utara