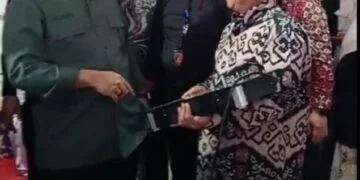IMBCNEWS | Jakarta, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara penghasil produk minyak sawit dunia, namun saat melakukan pemasaran ke benua Eropa, sering mendapatkan “diskriminasi” atau perlakuan berbeda , ataupun penolakan sehingga menghambat kinerja peproduk sawit dari kedua negara.
Pengamat lingkungan mengatakan, pemasaran produk sawit di pasar global dari Indonesia dan Malaysia jika kedua negara dapat tetap menjaga kelestarian hutan, karena yang dipersoalkan oleh para pecinta lingkungan yang diapresiasi komisi perdagangan Eropa adalah produsen sawit dari kedua negara belum menjaga hutan lestari secara baik.
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, belum lama ini sepakat membentuk Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit. (CPOC). Apakah dewan tersebut akan mampu memerangi apa yang diklaim kedua negara sebagai diskriminasi produk sawit dan bisa meningkatkan pasar sawit di dunia, masih menjadi tanda tanya.
VOA Indonesia Selasa melansir bahwa, Kepala Kampanye Hutan Greepeace Indonesia Kiki Taufik mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo untuk memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit ketika bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, menimbulkan pertanyaan besar di benak masyarakat internasional mengenai komitmen pemerintah Indonesia dalam menghentikan deforestasi hutan.
Kiki menjelaskan, Presiden Jokowidodo tidak menyebut secara gamblang mengenai kebijakan Uni Eropa yang menetapkan Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang menyebabkan penolakan produk kelapa sawit dari Indonesia. Namun, ia menduga pernyataan diskriminasi yang dilontarkan Jokowi mengarah kepada kebijakan Uni Eropa itu.
Kiki berpendapat, seharusnya pemerintah Indonesia tidak menganggap EUDR sebagai tindakan yang diskriminatif, karena sejatinya pengurangan deforestasi hutan merupakan komitmen global, termasuk Indonesia. Selain itu, katanya, dalam aturan EUDR, produk komoditas yang dilarang bukan hanya sawit. Tetapi mencakup produk komoditas yang dianggap menyebabkan deforestasi hutan seperti kopi, karet, kedelai dan sebagainya. Selain itu, regulasi tersebut juga melarang komoditas yang dihasilkan lewat deforestasi hutan setelah 2020.
“Jadi regulasi ini melarang komoditas yang dihasilkan lewat deforestasi setelah 2020, atau yang tidak memenuhi syarat ketertelusuran rantai pasokan untuk memasuki pasar Uni Eropa. Jadi pelaku usaha sawit di Indonesia seharusnya tidak terlalu sulit. Cukup membuktikan sudah tidak ada deforestasi di konsesi mereka setelah tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan EUDR ini,” tuturnya.
EUDR, menurutnya, seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman, tetapi momentum yang bagus bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa memang sudah tidak terjadi deforestasi hutan setelah 31 Desember 2020. Berdasarkan catatan Greenpeace Indonesia, laju deforestasi hutan dari 2019 hingga 2021 cenderung menurun, meskipun faktor penyebabnya patut dipertanyakan.
“Jadi satu pihak Indonesia mengklaim bahwa deforestasi turun, di satu pihak (Uni Eropa bilang) ya sudah ayo buktikan sawitnya bebas (deforestasi hutan). Tapi Indonesia tiba-tiba berpikir bahwa oh tidak bisa (menganggap diskriminasi). Jadi kan tanda tanya dong, benar gak deforestasinya turun?,” jelasnya.
Lebih jauh, Kiki menyatakan, produk sawit bisa menjadi sebuah produk komoditas yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Greenpeace Indonesia dan Uni Eropa, kata Kiki, sebenarnya tidak anti terhadap produk yang dihasilkan dari kelapa sawit. Bahkan, katanya, jika dibandingkan dengan komoditas lain, sawit membutuhkan lahan lebih kecil sehingga keefektifan dan produktivitasnya sebagai sumber minyak pun lebih bagus.
Lalu bagaimana caranya agar produk dari kelapa sawit dapat diterima di Eropa dan menjadi sebuah produk yang berkelanjutan? Menurutnya, pemerintah dan pengusaha sawit harus fokus kepada lahan yang sudah tidak berhutan, dan tidak membuka kebun sawit di wilayah gambut karena akan mudah terbakar.
Selanjutnya, harus ada bukti yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi land grabbing atau pemaksaan penguasaan lahan oleh perusahaan sawit dalam proses pembukaan kebun kepala sawit. Selain itu, perusahaan sawit juga harus memastikan tidak ada lagi eksploitasi terhadap para pekerjanya.
“Pastikan itu, kemudian buat sistem monitoringnya sehingga masyarakat di belahan dunia manapun akan paham dan akan confident, bahwa sawit yang dikonsumsi itu ramah lingkungan, tidak terlibat dengan deforestasi, dia tidak dibangun di wilayah gambut, tidak terlibat dengan perebutan hak masyarakat adat, kemudian juga tidak mengeksploitasi pekerja. Itu kan sistemnya, dan tata kelola sawit yang kita kejar,” tegasnya.
“Selama ini proses monitoring kan selalu tertutup, harusnya terbuka. Ini yang menjadi titik tekan bahwa di sini kan sebenarnya ini momentum untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan transparansi. Jadi transaparansi yang saya sampaikan harusnya diwujudkan setelah ada ada undang-undang ini,” katanya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai keputusan Indonesia dan Malaysia dalam membentuk CPOC merupakan langkah strategis. Bahkan, menurutnya, pembentukan persekutuan antara Indonesia-Malaysia ini akan meningkatkan bargaining position (posisi tawar menawar) kedua negara agar produk kelapa sawitnya bisa diterima Uni Eropa.
“Pembentukan persekutan dengan Malaysia saya kira bagus dalam rangka meningkatkan bargaining position, kemudian untuk meningkatkan ekspor sawit, atau olahan dari sawit dan seterusnya. Saya kira ini cukup bagus dan efektif, karena Indoensia dan Malaysia dua negara yang penghasil sawit terbesar di dunia,” kata Fahmy.
IMBCnews/voa/sumber diolah/